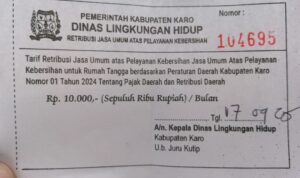MEDAN, SUMUTBERITA.com – Pegiat HAM dan Demokrasi, Kristian Redison Simarmata menyoroti pernyataan Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon yang menyatakan: “Tidak ada bukti pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998”. Klarifikasi itu disampaikan di Jatinangor pada 14 Juni 2025.
Ia menilai, pernyataan itu mungkin terlihat hanya seperti komentar ringan atau sekadar pendapat pribadi. Tetapi, kata Kristian, perlu digarisbawahi bahwa pernyataan itu dilontarkan Fadli Zon ketika negara sedang merevisi buku sejarah nasional.
“Artinya, ucapan itu berpotensi menggeser memori publik dan menutupi salah satu kejahatan paling brutal pasca-reformasi,” kecam Kristian dalam keterangan tertulisnya, Selasa (1/7/2025) dikutip dari tribunmedan.
Yang jadi inti persoalan, sebut Kristian, ketika pemerintah menyangkal fakta berdarah, kebenaran berubah menjadi opini, dan keadilan ambruk bersama ingatan korban. Yang perlu diingat oleh Fadli Zon dan masyarakat bahwa dasar penyebutan “pemerkosaan massal” berdasar pada bukti negara sendiri.
“Laporan resmi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk Presiden RI pada Oktober 1998 telah mengonfirmasi 85 kasus kekerasan seksual. Di mana 52 di antaranya pemerkosaan terhadap perempuan Tionghoa,” ungkap Kristian.
Temuan tersebut juga diperkuat Komnas Perempuan yang lahir melalui Keppres No. 181 Tahun 1998 dan menilai pola serangan bersifat sistematis dan rasial. Pelapor Khusus PBB, Radhika Coomaraswamy, setelah kunjungan lapangan November 1998, menyebut kekerasan tersebut “meluas dan disengaja”.
“Singkatnya, negara dan dunia internasional sudah memverifikasi tragedi itu 27 tahun silam,” sebut Kristian.
Menurutnya, dengan fakta selugas itu, bagaimana mungkin seorang pejabat publik berkata: “tak ada bukti”. Sebab, kata dia, ini bukan sekadar kekeliruan, melainkan denialisme, yakni upaya sadar menghapus catatan sejarah.
“Parahnya lagi, penyangkalan itu dilontarkan di tengah penyusunan buku teks sekolah. Jika narasi “tak ada pemerkosaan massal” masuk kurikulum, jutaan pelajar akan mempelajari sejarah palsu, dan jerih payah penyintas menuntut keadilan runtuh seketika,” ucapnya.
Selama 27 tahun, kata Kristian lagi, mayoritas penyintas memilih diam demi menahan stigma. Trauma, rasa bersalah, hingga gangguan stres pasca-trauma, masih mereka tanggung tanpa layanan pemulihan memadai. Ia menuding, pernyataan Fadli Zon bukan sekadar kesalahan akademik, namun memperdalam luka, memicu re-traumatisasi, dan mengirim pesan pedih: “Negara tak mengakui penderitaanmu”.
Padahal, ungkapnya, Komnas HAM telah memasukkan kasus Mei 1998 ke dalam daftar pelanggaran HAM berat. Namun hingga kini tidak satu pun pelaku kekerasan seksual diadili. Saat pejabat negara menyangkal skala kejahatan, peluang penuntutan makin tipis.
“Padahal, dalam hukum internasional, kekerasan seksual yang sistematis terhadap kelompok etnis, tergolong kejahatan terhadap kemanusiaan. Menolak fakta berarti memberi impunitas abadi kepada pelaku,” kecam Kristian.
“Fadli Zon menyebut penulisan sejarah harus “mempersatukan” bangsa dalam tone “positif”. Itu mantra lama Orde Baru: yang membersihkan catatan kelam demi stabilitas semu. Problemnya jelas, bahwa persatuan tanpa kebenaran melahirkan bangsa yang rapuh, bergelora di bawah. Demokrasi tidak dibangun di atas amnesia, ia bertumpu pada kejujuran sejarah,” tuturnya.
Lebih jauh, ia mempertanyakan: jika pemerkosaan massal 1998 bisa dihapus, apa jaminan peristiwa Talangsari, Tanjung Priok, atau Semanggi tidak bernasib sama? Menurutnya, sejarah Indonesia memang penuh luka, tetapi meng-edit kenyataan demi “citra positif”, justru membuka pintu bagi penyangkalan berantai.
“Hari ini Mei ’98, besok mungkin 1965. Di ujung jalan, kita hanya memiliki buku sejarah serba putih, bersih dari konflik, dan kosong dari pelajaran moral,” ucapnya.
Tanggung Jawab Pada Publik
Dalam melakukan revisi sejarah, Kristian menyarankan pemerintah harus berlandaskan beberapa langkah konkret di antaranya:
(1) Audit terbuka buku sejarah. Artinya: proses revisi teks wajib transparan. Komunitas akademik, penyintas, dan organisasi masyarakat sipil harus mendapat akses ke draf, metodologi, dan sumber rujukan;
(2) Pengakuan dan preparasi. Dalam hal ini, pemerintah harus menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM 2012: mengakui publik bahwa pemerkosaan massal terjadi, memulihkan hak korban, serta menjamin layanan kesehatan fisik-psikis;
(3) Pengadilan dan rekonsiliasi. Dalam hal ini, Kejaksaan Agung harus bergerak menuntaskan berkas Komnas HAM. Tanpa pengadilan, retorika “persatuan” hanya akan memperpanjang daftar impunitas;
(4) Pendidikan kritis. Artinya: kekerasan berbasis gender dan rasial harus diajarkan apa adanya di sekolah, bukan untuk menanamkan kebencian, tetapi agar generasi mendatang paham bahaya intoleransi dan otoritarianisme.
Kristian menegaskan, sejarah bukan dongeng untuk meninabobokan bangsa. Sejarah merupakan peta moral agar tragedi tak terulang. Menyangkal pemerkosaan massal Mei 1998, sama saja menolak kemanusiaan para korban dan menghapus fondasi keadilan.
“Bangsa yang besar, bukan bangsa yang lupa. Melainkan yang berani menatap luka, mengaku salah, lalu bergerak memulihkan. Karenanya, seorang menteri seharusnya berbicara dengan data, suara penyintas, dan tuntutan publik terhadap keadilan. Bila negara bersikeras menghapus luka itu, kita berisiko kehilangan lebih dari sekadar ingatan. Kita kehilangan arah moral sebagai Republik,” pungkasnya.
EDITOR: RED